Semua orang merasakan waktu, tetapi kebanyakan tidak mempertanyakan hal itu karena mereka mengalami setiap hari dan sangat intim (Fraser, 1987: 17-22). Jika kita ingin memahami sifat waktu, maka renungkanlah pertanyaan-pertanyaan mendasar ini:
• Apakah waktu benar-benar nyata?
• Bisakah kita menghentikannya?
• Bisakah kita membalikkannya?
• Apakah aliran waktu bersifat universal, atau hal itu hanya terkait dengan pengamat?
• Kapan waktu berawal, dan apakah ia memiliki akhir?
• Apakah ada waktu objektif, atau ia hanya suatu konstruksi dari imajinasi kita?
• Apakah ada hubungan antara ruang dan waktu?
• Bagaimana struktur waktu?
• Apakah waktu itu kontinu atau diskrit?
• Apakah arti dari kata “sekarang” dan “sebentar”?
• Mengapa waktu bergerak ke masa lalu?
• Bagaimana realitas masa depan?
Pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi subjek filsafat, fisika, dan kosmologi selama berabad-abad dengan sedikit kemajuan dalam menemukan jawabannya. Pertanyaan: “Apa itu waktu?”, tidak berbeda seperti pertanyaan: “Apa itu cinta?”; karena ia adalah sesuatu yang semua orang bisa merasakannya tapi tidak ada yang dapat memberikan definisi dengan tepat atasnya. Jika Anda mengajukan pertanyaan kepada banyak orang tentang waktu, pasti akan mendapatkan banyak jawaban. St. Augustine dalam Confessions bertanya, “Apa itu waktu?” Ketika tidak ada yang bertanya kepadanya, ia mengetahui; ketika seseorang bertanya kepadanya, ia tidak mengetahuinya.
Pemahaman mengenai waktu sangat penting dari sudut praktis di mana orang membutuhkan informasi untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa besar seperti banjir dan waktu panen, dan dari sudut filosofis didasarkan pada rasa ingin tahu dan cinta terhadap pengetahuan. Banyak agama dan aliran filsafat mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang waktu. Beberapa agama dan aliran filsafat mempertimbangkan waktu sebagai lingkaran tanpa awal atau akhir, ada juga yang menganggapnya sebagai linier dengan eksistensi pada masa lalu dan masa depan yang tak berbatas, dan ada pula yang menganggapnya sebagai imajiner karena eksistensi nyata adalah gerakan atau materi fisik saja.
Konsep waktu diperlukan ketika kita bertanya tentang kronologis suatu peristiwa dan durasinya. Dan karena hidup manusia dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang beragam jenisnya sehingga waktu memiliki tanda atau simbol pada semua aspek kehidupan. Beberapa contohnya seperti: proses penuaan secara biologis, ketepatan waktu dalam mekanika, arah waktu dan entropi dalam termodinamika, dan variasi waktu psikis yang dirasakan seseorang ketika menunggu sesuatu atau peristiwa. Oleh karena itu, waktu diperlukan untuk memahami realitas pada berbagai bidang yang terkait erat dengan fisika, biologi, psikologi, dan kosmologi.
Selama abad terakhir, seiring dengan konsep baru yang revolusioner dalam fisika dan kosmologi serta teknologi modern, akurasi ketepatan waktu menjadi sangat penting karena merupakan acuan bagi gerakan-gerakan yang sangat rumit—misalnya berbagai bagian mesin—karena diperlukan sistem kerja sama secara koheren. Pentingnya peristiwa waktu di Bumi dan di ruang angkasa telah disempurnakan oleh mesin yang mengukur ketepatan waktu seperti jam elektronik, jam atom, dan pulsar yang memancarkan gelombang radio pendek secara berkala dengan presisi sangat tinggi. Tetapi meskipun konsep-konsep abstrak tentang waktu seperti “perjalanan waktu” dan “kelengkungan waktu” yang dibawa oleh teori Relativitas, konsep modern kita mengenai waktu biasanya cukup praktis karena semuanya dilakukan sesuai jarum jam. Bahkan, teori fisika dan kosmologi modern telah menambahkan banyak pertanyaan dan paradoks tentang waktu daripada menjawabnya (Grunbaum, 1971, 195:230).
Sekarang kita dapat mengetahui dua aliran utama yang bertentangan secara filosofi mengenai waktu:
1. Rasionalis (realistis) yang memiliki pandangan berdasarkan pemahaman dunia fisik.
2. Idealis (dapat dikatakan irasional) berdasarkan pandangan metafisika.
Rasionalis percaya bahwa pikiran adalah kekuatan yang paling kuat dari manusia dan mampu memahami segala sesuatu di dunia, sedangkan irasionalis mempertimbangkan dunia, termasuk waktu, sebagai sesuatu di luar kemampuan pikiran. Menurut Idealis, tidak ada yang terlepas dari pikiran, termasuk waktu. Oleh karena itu, Idealis percaya bahwa waktu dikonstruk dalam pikiran dan tidak memiliki eksistensi terpisah darinya.
Konsep Waktu dalam Filsafat Yunani
Sejak masa Homer, kata Yunani chronos digunakan untuk merujuk kepada waktu. Chronos adalah dewa Yunani yang ketakutan terhadap anak-anaknya karena akan mengambil alih kerajaannya, sehingga ia memakan mereka satu persatu—seperti waktu yang membawa sesuatu menjadi eksistensi dan kemudian eksistensi tersebut kembali datang kepada waktu.
Kita sudah mengetahui dua aliran berlawanan mengenai waktu yang berbeda dengan pemikiran Plato dan Aristoteles. Plato menganggap waktu dibuat dengan dunia, sementara Aristoteles berpandangan bahwa dunia diciptakan dalam waktu yang merupakan perluasan tak terbatas dan berkesinambungan. Plato mengatakan, “Waktu muncul bersama-sama dengan surga, karena keduanya menjadi secara bersamaan” (Cornford, 1997:99).
Aristoteles percaya bahwa proposisi Plato memerlukan titik waktu sebagai awal waktu yang memiliki waktu sebelumnya. Gagasan ini tak terbayangkan bagi Aristoteles sesuai dengan pendapat Demokritus mengenai konsep waktu tak diciptakan dan mengatakan: “Jika waktu adalah gerakan abadi, maka ia juga harus abadi karena waktu adalah anggota gerak. Mayoritas filsuf, kecuali Plato, menegaskan keabadian waktu. Waktu tidak memiliki batas (awal atau akhir), dan setiap saat adalah awal dari waktu masa depan dan akhir dari masa lalu” (Lettinck, 1994: 562).
Waktu menurut Aristoteles adalah kontinum, dan selalu dikaitkan dengan gerakan, dengan demikian tidak dapat memiliki awal (Lettinck, 1994: 241-259, 361). Di sisi lain, Plato menganggap waktu sebagai gerakan melingkar dari langit (Cornford, 2004: 103), sedangkan Aristoteles mengatakan bahwa itu bukan gerakan waktu melainkan ukuran gerak (Lettinck, 1994: 351, 382, 390). Aristoteles jelas menghubungkan waktu rasional dan gerakan, tetapi di sini masalah timbul karena waktu adalah seragam, sementara beberapa gerakan ada yang cepat dan lambat. Jadi, kita mengukur gerak oleh waktu karena seragam—jika tidak demikian maka tidak dapat dikatakan sebagai ukuran. Untuk mengatasi masalah ini, Aristoteles mengambil gerakan bola surgawi sebagai referensi, dan semua gerakan lainnya beserta waktu diukur menurut gerakan ini (Badawi, 1965: 90). Di sisi lain, Aristoteles menganggap waktu sebagai khayalan karena itu adalah masa lalu atau masa depan dan keduanya tidak ada, sementara saat ini bukan bagian dari waktu karena tidak memiliki ekstensi (Lettinck, 1994: 348).
Kita akan melihat bahwa Ibn Arabi sependapat dengan pendapat Aristoteles bahwa waktu tak berujung dan ia adalah ukuran gerak, tetapi Ibn Arabi tidak menganggap waktu bersifat kontinum. Di sisi lain, Ibn Arabi setuju dengan Plato bahwa waktu diciptakan dengan dunia. Bahkan Plato menganggap waktu telah diciptakan, tetapi Aristoteles menolak pendapat ini karena ia tidak bisa membayangkan titik awal untuk dunia maupun waktu. Hanya setelah teori Relativitas Umum pada tahun 1915 lahir yang memperkenalkan ide “waktu melengkung”, bisakah kita membayangkan waktu yang terbatas tetapi kelengkungan waktu sebagai tanda memiliki awal. Dengan hal ini, kita bisa menggabungkan pandangan Plato dan Aristoteles yang berlawanan. Namun, Ibn Arabi melakukan hal tersebut tujuh abad sebelumnya, dan ia juga secara eksplisit berbicara tentang kelengkungan waktu, lama sebelum Einstein mengeluarkan teorinya.

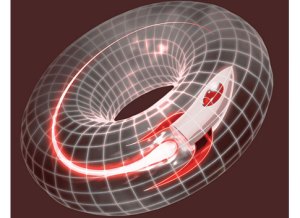 TEORI Albert Einstein, mengatakan bahwa dalam perhitungan-perhitungan ilmiah, manusia tidak hanya berurusan dengan tinggi, lebar dan panjang; melainkan juga dengan satu dimensi lain, yaitu waktu. Hidup ini terasa lama karena manusia terikat oleh ruang dan waktu dan terikat pada pola Logika Manusia. Padahal, di dalam kontek Logika Tuhan, maka sebenarnya hidup manusia hanya “satu detik” saja.
TEORI Albert Einstein, mengatakan bahwa dalam perhitungan-perhitungan ilmiah, manusia tidak hanya berurusan dengan tinggi, lebar dan panjang; melainkan juga dengan satu dimensi lain, yaitu waktu. Hidup ini terasa lama karena manusia terikat oleh ruang dan waktu dan terikat pada pola Logika Manusia. Padahal, di dalam kontek Logika Tuhan, maka sebenarnya hidup manusia hanya “satu detik” saja.